13 #1
Hanya senyuman ringan. Tak lebih. Tepatnya di mukaku yang semakin kusam di makan waktu, semakin kusut dan hitam di bakar matahari. Dari sambutan kepala sekolah yang membosankan, sampai puncak pentas seni seharusnya menjadi momentum penting bagiku. Tetapi, hanya kusambut dengan senyuman masam yang kupasang paksa di mulutku. Kegembiraan yang semu. Siang bolong yang melelahkan.
SMS mereka seakan sudah mereka rencanakan untuk membunuhku secara perlahan. Tak hanya teman sakelas, teman se-organisasi pun meminta doa agar lolos test masuk perguruan tinggi yang mereka dicita-citakan. Jakarta, bandung, Semarang, Jogja, Surakarta, bahkan ada juga yang meminta amplop saat pernikahannya nanti, dua minggu mendatang. Menyebalkan. Mereka seakan buta dan pura-pura buta akan keadaanku yang tak jelas arah vektornya ini.
Angin yang seharusnya bertanggung jawab atas gesekan dedaunan yang membuat semakin onar keadaan. Berisik! Mana tak ada satupun bintang yang nongol malam ini, seakan awan mendung mencaploknya habis seperti buta ijo memakan bulan saat gerhana menurut pemahaman jawa kuno. Malam macam apa ini! umpatan tak jelas kesana-kemari hatiku seolah menjadi curhatan hati kepada nyawaku, yang kini lelah menemani ragaku, yang agak gendut dan relative pendek ini.
Mana mungkin aku menjadi polisi, push up sepuluh kali aja dah membuat cengkehku keluar, cengkeh yang kumakan saat sekolah SMP dulu. Belum lagi tinggi badan yang tak sesuai ketentuan, ditambah kacamata-minus satu setengah yang melekat erat, seakan sudah menjadi anggota mataku. Umpatan itu sekarang berganti menuju diriku sendiri. Manusia macam apa aku ini.
Langkah simbok membangunkan lamunanku dengan menghadiahkan secangkir teh manis dan ubi rebus kesukaanku. Beliau langsung duduk disampingku, tepatnya di kursi panjang peninggalan kakek tempatku berbaring. Aku pun mulai bangun.
“kamu ngalamun apa Zul. Simbok lihat dari tadi siang kok kamu duiem banget!”
Dalam bahasa jawa, mengucapkan kata yang disisipkan huruf “U” bermakna sangat atau berlebihan. Tak cukup dengan kata banget. Misalnya, kamu ini kok goblok banget!. Berarti masih terhitung ” goblok” yang biasa-biasa saja. Tapi kalau diganti, kamu ini kok guoblok banget! Itu baru goblok yang kelewatan.
“emm….. nggak mbok. Lagi mencoba melihat masa depan”, jawabku sekenanya.
Simbok pun tersenyum, aku tak tahu apa arti senyumannya. Yang ku tahu aku melihat raut mukanya yang sudah tua dan lukisan garis khatulistiwa-kesusahan di setiap bagian kedua pipinya.
“kamu ini kok aneh! Melihat masa depan yang kayak apa?”
Aku pun langsung bingung. Apa yang harus kulihat dari masa depanku yang sudah-sudah tak jelas ini. aku pun menyesal, menyuguhkan jawaban yang tak kutahu apa jawaban selanjutnya.
“masa depanku yang tak jelas mbok. Temen-temen pada nerusin sekolah. Lha aku?”, ku akhiri dengan pertanyaan yang mungkin menyakiti perasaan simbok. Maaf mbok.
“lho, lho, lho… sejak kapan anak simbok jadi pesimis gitu? Siapa yang ngajarin?”, sindir simbok.
“sapa yang tahu masa depan Le?. Jangankan kamu, Orang yang pinter bagaimanapun, gak akan bisa melihat masa depan kayak apa!”, lanjutnya
Thole adalah panggilan akrab orang jawa, sama seperti panggilan anakku, putraku atau sebagainya. Nasihat singkat, padat dan terikat simbok seakan menggetarkan hatiku yang hitam ini. membasuh di setiap tepi-tepinya, dan kini seolah mulai memutih. Sebuah pertanyaan retoris di hadapanku tak sanggup kujawab. Simbok memang pandai menciptakan kalimat retoris. Aku tertunduk patuh dengan menyeka timbunan embun mataku yang sejak tadi menetas.
“simbok ngerti. Kamu iri sama temen-temenmu kan, yang bisa ngelanjutin sekolah? Atau kayak Bagas yang mewarisi pabrik tahu bapaknya.”
“bukannya sebelum pergi, bapakmu dulu pernah ngomong . ‘Kamu itu jangan pesimis dengan keadaan kita yang sekarang, Zul. Kamu anak bapak satu-satunya, dan bapak yakin, kamu juga satu-satunya orang yang akan merubah keadaan kita. Bukan bapakmu, bukan juga simbokmu!”, lanjut beliau.
Nyanyian jangkrik yang tak teratur menghantarkanku pada dunia mimpi yang jauh lebih indah daripada dunia nyataku sekarang. Jauh lebih nyaman dan damai. Polusi cahaya yang mulai memadati kampung sejak revolusi listrik masuk desa, seakan mengganggu setiap malamku. Mengganggu pesona kunang-kunang yang menyalakan senter alaminya, mengganggu keagungan ciptaan Maha Karya akan jagad raya yang kaya dengan bintang dan bulan semata-wayang. Dan akhirnya, kutak tahu batas antara sadar dan tidurku.
*******
“Zul! Zul! Zulfahmi!”
Sepertinya ada yang memanggilku keras. Segera kubaca teriakan itu. Ah, Margono Sitohang. Anak keturunan Batak yang lahir dan besar di suku Jawa, temanku sejak kecil, dan anehnya kami selalu satu kelas walau dia lebih tua satu tahun dariku. Aku pun tak tahu dan tak mau tahu kenapa dia bisa nyasar di perkampungan jawa ini.
“Apa Gon?”, jawabku lemas. Kelelahanku ngarit, mencari rumput, sudah cukup membuatku malas akan aktivitas lainnya. Apalagi ngobrol dengan Margono.
“ada kerjaan, Zul! Cocok buat kamu. Mau gak!”, katanya yang mulai mendekatiku.
“kerjaan apaan?”, sambungku
“di Jogja, Zul. Bagas ngasih aku tawaran job buat bikin toko fotokopian di deket kampusnya. Dia mau aku dan kamu yang ngurusin. Masalah honor, gampang katanya.”, kata Gono semangat
“itupun kalau kamu gak nolak!”, cetusnya datar.
Sejenak otakku dibuatnya berpikir. Memikirkan kesempatan tawaran itu.
“aku tak izin simbokku dulu ya, Gon? Baru nanti aku jawab.” Singkatku
“jangan lama-lama mikirnya. Nanti keburu Bagas berubah pikiran!”, katanya menasihati.
“yo wis lah. Aku tak ngarit dulu. Wah, hijau banget rumputnya? Ngarit dimana?”, lanjutnya bertolak dariku.
Tak kujawab pertanyaan akhirnya. Pikiranku masing meneropong akan tawarannya. Terbayang wajah simbok yang semakin menghitam terpanggang matahari. Aku akan berangkat ke kota dan meninggalkan simbok sendirian dirumah. Tak terbayang siapa yang menemaninya minum wedang teh dan ubi rebus. Siapa yang diajaknya ngobrol mengenai keadaan pasar setiap Legi dan Wage pagi, dan pastinya siapa yang menghabiskan jajanan pasar saat tiba di rumah.
Ah, yang terpenting, bagaimana caranya aku bisa meminta izin kepada beliau untuk menerima tawaran si-Batak nyasar itu. Aku harus bisa bernegoisasi dengan simbok. Harus!
*******
“Yau dah Le. Kalau itu keinginanmu gek berangkat sana. Temui Margono. Mungkin saja, tawaran Bagas bisa jadi batu loncatan cita-citamu.”, ujar simbok singkat.
lagi-lagi nasihat singkat simbok membersihkan hitamnya hatiku. Yaa, batu loncatan! Ini bisa menjadi jembatan penghantar cita-citaku. Ucapan simbok selalu menjadi penyemangat masa depanku. Sepertinya tak ada ucapan simbok yang sia-sia. Aku tak pernah mendengar beliau mengeluh sedikit pun sejak ditinggal bapak dua tahun yang lalu. Yaa, bapak meninggal ditanah air orang lain, yang hingga kini tak ada satupun pernyataan kenapa penyebabnya, bahkan dimana pemakamannya. Seakan orang kecil macam kami tak berhak menanyakan hal kecil macam itu kepada para penguasa. Menurut mereka, masalah ini hanyalah seperti bangkai tikus yang mati di jalan pasar yang akhirnya akan habis baunya diinjak-injak tukang sayur, tukang angkut, dan ibu-ibu pembeli. Tak penting.
Tak ada salahnya mencoba mengadu nasib di kota, pikirku. walaupun hanya sebagai pegawai fotokopi. Yaa, yang penting halal. Daripada para penguasa yang diberi rumah dinas, mobil dinas, laptop dinas, perjalanan dinas, yang semua itu dijawab seirama “Demi Kepentingan Rakyat!”. PRÊT! Persetan dengan ucapan mereka semua! Busuk! Dah ketahuan korupsi, masih saja senyum-senyum dan angkat bicara di kamera wartawan. Gantung saja mereka, pak presiden!. Negeri ini gak butuh orang macam mereka. “Tak ada gunanya mereka yang ada di senayan!”. Itulah kata para mahasiswa saat demo kemarin. Namun, menurutku ada gunanya kok mereka yang ada di senayan. Yaa, minimal mengurangi pengangguran! Ha ha, umpatanku yang tak jelas sekarang beralih ke politik rupanya, ujar hatiku yang mulai menghitam lagi.
*******
Bersambung...
oleh : Arif Setiyanto
oleh : Arif Setiyanto

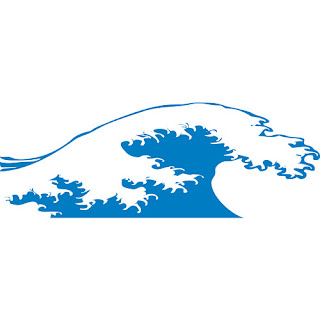
%20(1).png)
